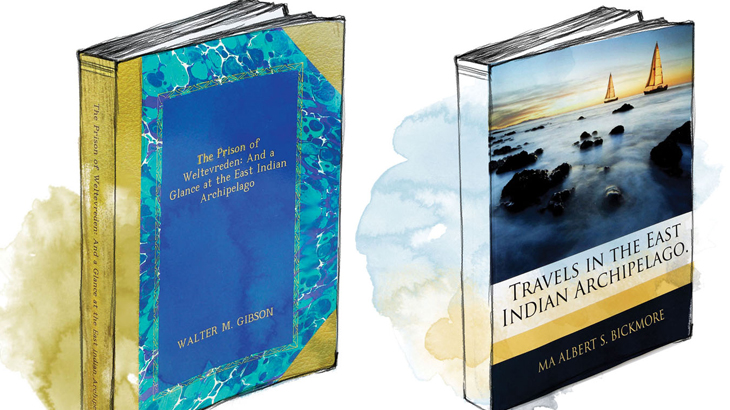Dunia tengah dihajar krisis ekonomi yang hebat ketika Parada Harahap melawat ke Jepang. Tapi justru di momen itulah dia melihat keajaiban. Pada 1930-an, pabrik-pabrik di Eropa rontok dan harga bahan mentah di pasar dunia terban. Bencana kemudian merembet dan memukul telak Hindia Belanda yang perekonomiannya ditopang oleh produksi bahan mentah.
Tapi, saat ekonomi dunia terkapar, Jepang justru segar-bugar. Di tengah harga-harga yang melambung, komoditas industri mereka justru berharga murah di Hindia Belanda. Ketika banyak pabrik di Barat gulung tikar, Jepang malah menggeliat dengan industrialisasi. Ada apa dengan Jepang? Bagaimana mereka bisa begitu cepat melesat mengejar Eropa?
Itulah sebagian pertanyaan yang hendak dijawab Parada Harahap dalam eksplorasinya di Timur, di negeri tempat matahari terbit. Parada menulis, “Di dalam tempoh jang sependek itoe dapat ia mengatoer negerinja sedemikian roepa, sehingga mendjadikan bangsa-bangsa di seloeroeh doenia terkedjut melihatnja.” Selama ini kaum bumiputra telah banyak melawat ke Barat, katanya, tapi dengan kemajuan pesat yang dialami Jepang sekarang, patutlah kita melawat juga ke Timur, belajar dari “saudara tua” yang lebih dekat.
Menoedjoe Matahari Terbit (Perdjalanan ke Djepang) menjadi buku yang patut dibaca guna mengetahui bagaimana orang Indonesia memandang Jepang pada periode itu. Buku yang diterbitkan pada 1934 ini merekam bagaimana Negeri Sakura menjadi magnet baru bagi kaum terpelajar. Dalam hampir 50 halaman pertama, Parada menggambarkan suasana di dalam kapal Jepang. Nagoya Maru merupakan kapal komersial yang tidak kalah mewah dibandingkan kapal-kapal Belanda, hanya saja tarifnya jauh lebih murah, demikian catat Parada. Pada halaman-halaman setelahnya, Parada mengenang kunjungannya ke pabrik-pabrik, contohnya Kawazaki Dokfabriek yang memproduksi kapal laut.

Di sela-sela turnya, Parada menyisipkan kisah sejumlah tempat wisata. Ketika di Kobe, Parada berpelesir ke Kobe Bij Nacht, kompleks hiburan malam yang menjadi pembicaraan koran-koran di Tanah Air. Saat di Osaka, dia mengunjungi museum yang mengoleksi benda-benda kerajaan Jepang. Parada juga sempat menikmati keindahan Gunung Fuji, singgah di kota tua yang dihuni istana di Nara, serta menyaksikan musim salju di Nikko.
Bagaikan penulis yang diutus Lonely Planet, Parada mencatat detail informasi seputar hotel, lengkap dengan tarifnya, transportasi menuju suatu tempat wisata, kuliner setempat, serta petuah bagi pelancong yang berencana ke Jepang. Dia menyarankan saudara-saudaranya menghindari periode November hingga Januari, karena Jepang sedang dilanda musim dingin yang menyengat. Datanglah antara Maret dan Mei, sewaktu “gadis, djanda, toea dan moeda keloear memetik kembang.”
Sebagai penulis, Parada merintis karirnya sebagai kerani di sebuah perusahaan perkebunan di Sumatera Timur, lalu menerbitkan majalah untuk golongannya: De Kranie. Usai menjadi redaktur Sinar Merdeka di Padang Sidempuan pada 1919-1922, dia berkecimpung di berbagai harian dan majalah, antara lain Benih Merdeka dan Hindia Sepakat. Setelah merantau ke Jawa, Parada bekerja sebagai reporter Sin Po. Pada 1924, dia mendirikan kantor berita Alpena dan mingguan Bintang Timoer. Saat bekerja di sinilah dia ke Jepang. Tidak banyak memang buku perjalanan tentang negeri asing yang ditulis orang Indonesia. Di antara yang sedikit itu, beberapa dikarang oleh jurnalis. Parada menyebut genre ini “ journalist pelantjongan.”
Jauh sebelum Jepang menjadi magnet, Barat telah lama memikat bumiputra. Demam lawatan ke Barat sepertinya dimulai sejak akhir abad ke-19 saat dr. A. Rivai meninggalkan Sumatera menuju Eropa, tapi sayang jurnalnya tak pernah sampai ke tangan kita dalam bentuk buku. Dokumentasi ekspedisi ke Barat pertama dibuat oleh Djamaluddin Adinegoro dalam bentuk empat jilid catatan perjalanan.
Adinegoro melawat ke Barat ketika kampungnya di Minangkabau digoyang gempa hebat. Padang Panjang dan Solok dikoyak berulang-ulang hingga luluhlantak. Sementara di pesisir, banjir hebat menggenangi Padang. Tidak lama kemudian, pemberontakan komunis meletus. Ketika kejadian-kejadian penting itu berlangsung, Adinegoro sedang di atas kapal yang membawanya ke Barat. Dia hanya sempat menuliskan keprihatinannya. “Betul malang rakjat Minangkabau,” tulis Adinegoro dalam Melawat ke Barat.

“Kitab ini ditoelis di kapal di tengah laoetan besar,” begitu catat Adinegoro dalam kisah yang direkamnya dari 1926 hingga 1929 itu. Bukunya yang dicetak pada 1930 merupakan antologi yang diterbitkan secara bersambung di koran Tanah Air. Dua dekade kemudian, Balai Pustaka menerbitkan ulang bukunya dan merangkumnya menjadi dua jilid saja. Bagian pertama berisi perjalanan dari Indonesia. Adinegoro bertolak dari Pelabuhan Tanjung Priok dengan menumpang kapal Belanda menuju Sabang, menyinggahi Singapura, Maladewa, Laut Merah, hingga menyeberangi Terusan Suez menuju Laut Tengah. Bagian kedua memuat kisahnya di Eropa: mengunjungi kota-kota di Prancis, lalu menyeberang ke Belgia.
Buku ketiga masih memuat kisahnya di Eropa: pengalaman memperdalam ilmu geografi di Utrecht, kartografi di Würzburg, dan geopolitik di Munich. Buku keempat diberi judul tersendiri, Kembali dari Perlawatan. Adinegoro mudik ke Indonesia via Italia. Dia membawa pembaca ke Mesir yang dihuni tanah jajahan Italia, Eritrea. Dari sana, dia singgah di India kala Gandhi sedang gigih membebaskan India dari kolonialisme.
Berbeda dari Parada, bahasa Adinegoro cenderung lebih puitis. Kalimat-kalimatnya panjang, tertata apik, dan dihiasi banyak metafora. Destinasi-destinasi wisata di sepanjang perjalanan mendapat proporsi ulasan yang lebih besar dan deskripsi yang lebih hidup. Selain menjadi wartawan dan penulis cerita perjalanan, Adinegoro merupakan seorang pengarang roman. Dua buah novelnya, Darah Muda dan Asmara Jaya, dianggap membawa pembaruan dalam konstelasi novel zaman kolonial.
Adinegoro umumnya menggambarkan Barat dalam sisi yang baik. Tentang Jerman, tempat dia belajar selama tiga tahun, Adinegoro menulis: “Negeri itu baik untuk orang belajar, dengan terbuka menerima setiap yang datang, dan tiap yang meninggalkannya akan bersedih hati.” Dia menampilkan Barat dengan penuh takjub, layaknya seorang anak jajahan yang terpukau. Memang ketakjuban kaum intelektual Indonesia pada Barat pada masa itu sedang menggejala, walau sebenarnya Ketertarikan mereka mengidap ambivalensi: benci pada Barat, namun juga hendak seperti Barat.

Dari karya Parada dan Adinegoro, kita menangkap stimulus yang bertujuan membangkitkan gairah orang Indonesia mengejar kemajuan negeri-negeri asing. Keduanya mafhum, kemajuan suatu bangsa mesti dicapai dengan cara belajar kepada bangsa lain yang telah lebih dulu maju—dan melawat adalah salah satu cara untuk membuka mata kita pada dunia.
Pendekatan itu masih menyisakan jejaknya pada masa-masa awal kemerdekaan. Untuk itulah buku karya DN Aidit layak disimak. Laporan kunjungannya ke beberapa negara dikompilasi dalam buku Dari Sembilan Negeri Sosialis. Pada pertengahan Februari 1956, Aidit berkelana ke Uni Soviet, lalu berturut-turut ke RRC, Korea, dan Cekoslowakia.
Dia membesuk Ketua Mao ketika “kaum kapitalis beramai-ramai bermohon pada pemerintah supaja dirinja dilenjapkan sebagai klas agar dapat ambil bagian dalam pembangunan masyarakat sosialis.” Dalam eksplorasinya, Aidit menyatroni pabrik dan bercakap-cakap dengan buruh. Di Cekoslowakia, Aidit melaporkan: “Penghidupan Rakjatnja termasuk jang terbaik diantara negeri2 jang sudah madju, hampir tiap keluarga memiliki radio atau televisi.” Mereka telah punya mesin yang berjalan otomatis, yang paling modern pada masa itu. ”Lebih modern dari pada mesin2 Amerika,” kata Aidit lagi.
Aidit fokus pada sisi-sisi baik sosialisme dan komunisme. Sudut pandang ideologisnya bisa dimaklumi, karena dia melakukan perjalanan dinas sebagai Ketua PKI. Bukunya lebih ditulis sebagai alat propaganda, pemompa semangat bagi anggota PKI. Wajar jika guratan penanya nyaris tak menyisakan ulasan wisata.
Melangkah lebih jauh ke masa Orde Baru, Nasir Tamara terbang ke Iran pada Januari 1979 bersama Ayatollah Khomeini. Setiba di Iran, sebelum turun dari pesawat, Imam Syiah itu disambut jutaan rakyat yang mengelu-elukannya. Iran sedang bergejolak. Revolusi berada di titik nadir. Dalam buku Revolusi Iran yang terbit pada 1980, Nasir tidak mengupas tempat-tempat wisata yang membius mata. Pelancongan Nasir justru dipenuhi teriakan, penyanderaan, letusan senjata. “Seorang raja yang ditunjang oleh tentara No. 5 terkuat di dunia digulingkan tahtanya oleh rakyat tak bersenjata di bawah pimpinan seorang tua yang hampir 15 tahun berada di pengasingan,” begitu Nasir mendedahkan revolusi Iran.
“Shah ingin negerinya maju seperti negeri Amerika Serikat, Jepang atau Eropa. Tetapi kemajuan itu hanya mengarah pada pembentukan masyarakat konsumsi belaka,” tulis Nasir lagi dalam bukunya. Buku 446 halaman ini memang lebih terfokus pada tumbangnya rezim Shah dan kemunculan Khomeini sebagai “imam” yang berniat membawa Iran ke peradaban baru: tidak “Timur,” tidak juga “Barat.”
Tak lama setelah Nasir, Syafiq Basri, juga seorang wartawan, menginjakkan kakinya di Iran pada 1984, lima tahun setelah Revolusi Iran berkobar. Dia mengulas laju revolusi dan Iran yang belum kondusif. Bom meledak di stasiun kereta. Pembajakan pesawat masih terjadi. Syafiq datang saat warga kelas bawah sedang diperhatikan pemerintah Ayatollah. Mereka dipandang sebagai tulang panggung revolusi. “Kini pemerintah sedang menerapkan ekonomi kupon, setidaknya dua sistem kupon” tulisnya dalam Iran Pasca Revolusi: Sebuah Reportase Perjalanan. “Kupon untuk membeli jenis barang yang awet seperti gula, beras, sabun—dikelola oleh Bank Saderat Iran. Kedua, kupon untuk kebutuhan barang sehari-hari seperti daging, mentega, susu, rokok, ban mobil, kipas angin—disalurkan lewat mesjid”.
Dari Teheran, Syafiq melancong ke Pulau Majnoon yang dijulukinya pulau gila yang penuh nyamuk. Dia terbang ke Kashan, kemudian mengunjungi danau garam di barat Padang Pasir Kavir. Dia berkendara ke daerah-daerah yang dulu porak-poranda ketika revolusi mencapai puncaknya. Syafiq juga menyisir sungai-sungai yang mengering dan melewati tank-tank Iraq yang terhampar di sawah di Kota Ahvaz, selanjutnya ke Kut, Hoveizeh, dan Susangird yang rata dengan tanah.
Berbeda dari karya-karya lawas, buku perjalanan saat ini cenderung berformat panduan wisata. Niat penulisnya adalah membimbing kita bersenang-senang di negeri orang. Kita masih bisa mencium keinginan untuk belajar dari negara lain, tapi baunya kerap terlalu tipis.
Dipublikasikan perdana di majalah DestinAsian Indonesia edisi Nov/Des 2014 (“Kabar Asing“)